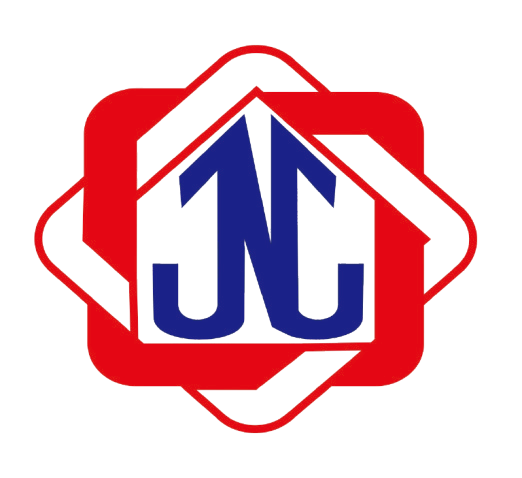Jakarta, Jaladrinews.com -Tim Nasional Indonesia menghadapi laga berat di Grup B ronde keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Arab Saudi. Pertandingan yang seharusnya menjadi ajang kebanggaan justru meninggalkan luka batin, bukan karena skor 2–3 atau peluang yang hilang, melainkan karena suara-suara dari tribun maya yang mengoyak kemanusiaan.
Ujaran rasis menimpa Sayuri bersaudara, Yakob dan Yance, setelah kekalahan dari Arab Saudi, 9 Oktober 2025 di King Abdullah Sport City. Akun media sosial mereka dibanjiri cacian, hinaan, dan kata-kata tak senonoh. Di antara ribuan komentar, sebagian besar berisi hujatan bernada rasis, menyamakan mereka dengan "kera", "monyet", dan "anjing".
Hanya karena satu momen, ketika Yakob Sayuri dianggap menarik baju pemain Arab Saudi, Feras Al-Buraikan, yang berujung penalti, mereka dijadikan kambing hitam kekalahan Timnas. Seolah satu kesalahan dalam permainan menjadi alasan untuk menumpahkan segala kebencian yang telah lama tertanam di sebagian hati suporter Indonesia.
Inilah ironi yang menyakitkan: ketika pemain Papua tak membela Timnas, mereka dicap tidak nasionalis; namun ketika mereka tampil dan tim kalah, mereka diserang dengan hinaan yang menelanjangi kebobrokan moral bangsanya sendiri.
Boaz Solossa pernah mengalami hal serupa. Ketika ia tak hadir membela Timnas, sebagian masyarakat menuduhnya tak mencintai Indonesia. Padahal Boaz sendiri pernah menjelaskan bahwa ia absen karena cedera patah kaki yang justru dialaminya saat membela Timnas, bukan saat memperkuat klubnya, Persipura. Tapi bagi sebagian orang, kebenaran tak penting, yang penting adalah menemukan kambing hitam, dan sayangnya, warna kulit sering kali menjadi alasan yang paling mudah.
Rasisme terhadap pemain Papua telah lama hidup dalam tubuh sebagian masyarakat Indonesia. Ia tak selalu hadir dalam bentuk teriakan di stadion; sering kali ia bersembunyi di balik sorakan, di balik emoji tawa, di balik komentar yang “cuma bercanda.” Namun di balik candaan itu, ada sejarah panjang diskriminasi yang membuat anak-anak Papua tumbuh dengan luka di tanah yang mereka cintai, di republik yang seharusnya melindungi mereka.
Banyak yang berteriak soal nasionalisme, tetapi melupakannya ketika berhadapan dengan perbedaan. Mereka mengaku mencintai Indonesia, tetapi gagal memahami bahwa Papua adalah Indonesia juga bukan sekadar bagian geografis, melainkan denyut nadi dari keberagaman itu sendiri. Nasionalisme itu menjadi topeng.
Nasionalisme sejati tidak tumbuh dari sorak sorai ketika menang, atau cacian ketika kalah. Ia tumbuh dari penghormatan yang tulus kepada sesama anak bangsa. Bila cinta tanah air tidak diiringi penghormatan terhadap kemanusiaan, maka yang tersisa hanyalah nasionalisme semu, nasionalisme yang berseragam merah putih, tetapi berhati binatang.
Sikap seperti ini tidak hanya terjadi di dunia sepak bola. Dalam banyak aspek kehidupan sosial dan politik, orang Papua kerap diperlakukan seperti “kerikil dalam sepatu”: dianggap bagian dari republik, tapi tak pernah benar-benar diterima. Ketika mereka berbicara tentang keadilan, mereka dicap separatis. Ketika mereka diam, mereka dilupakan. Di titik inilah, ideologi Pancasila yang selalu diagung-agungkan seakan kehilangan maknanya, hanya menjadi slogan kosong tanpa ruh kemanusiaan.
Apa yang terjadi pada Sayuri bersaudara bukan sekadar kasus individu, melainkan cermin buram dari bangsa ini. Mereka menelanjangi moralitas kolektif yang sedang sakit. Kita bisa membangun stadion megah, mencetak pemain hebat, dan berteriak “Garuda di Dadaku” sekeras mungkin, tetapi semua itu tak berarti bila di dada kita masih tersisa kebencian terhadap sesama warga negara sendiri.
Kita perlu jujur bahwa rasisme ini bukan soal sepak bola semata. Ia adalah penyakit sosial yang telah lama dibiarkan hidup dan diwariskan dalam percakapan, disebarkan lewat candaan, dan dipelihara lewat diam dalam rahim bangsa Indonesia.
Sepakbola seharusnya menjadi simbol persatuan, penghormatan, keberanian dan kemanusiaan, bukan warna yang menutupi kebencian. Jika bangsa ini ingin benar-benar disebut besar, maka kebesarannya harus diukur dari caranya memperlakukan manusia, bukan dari jumlah kemenangan, bukan dari teriakan di tribun, tetapi dari kemampuan menghargai setiap warga tanpa memandang warna kulit dan asalnya.
Ketika anak-anak Papua mengenakan seragam Merah Putih, mereka sedang mewakili bangsa ini. Namun ironinya, bangsa yang mereka wakili justru melukai mereka. Itulah rasisme yang berseragam Merah Putih, kebencian yang dibungkus cinta yang palsu, dan nasionalisme yang kehilangan jiwanya.